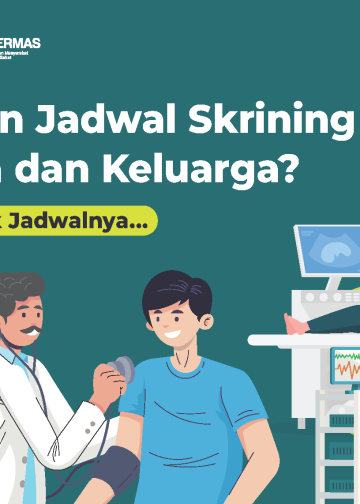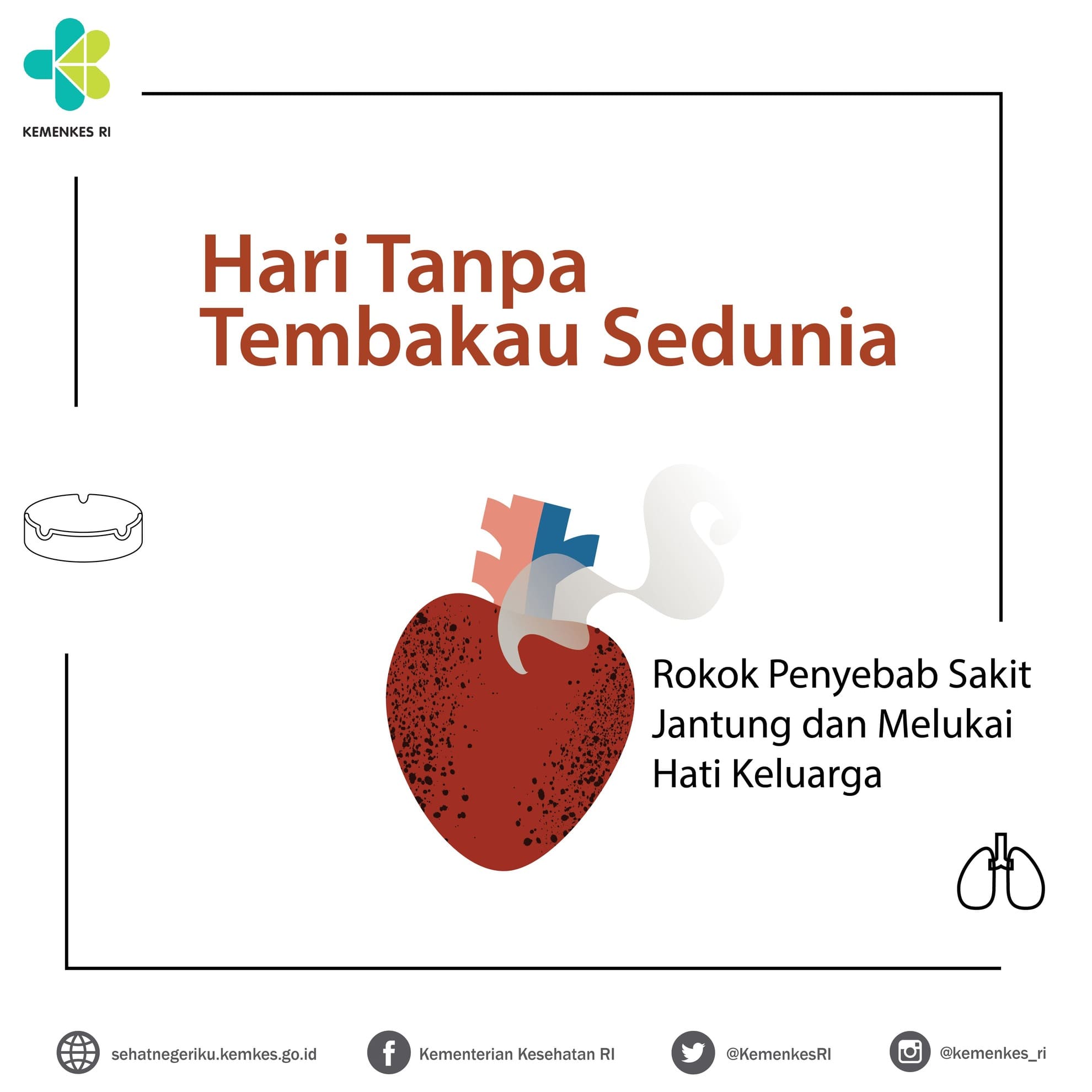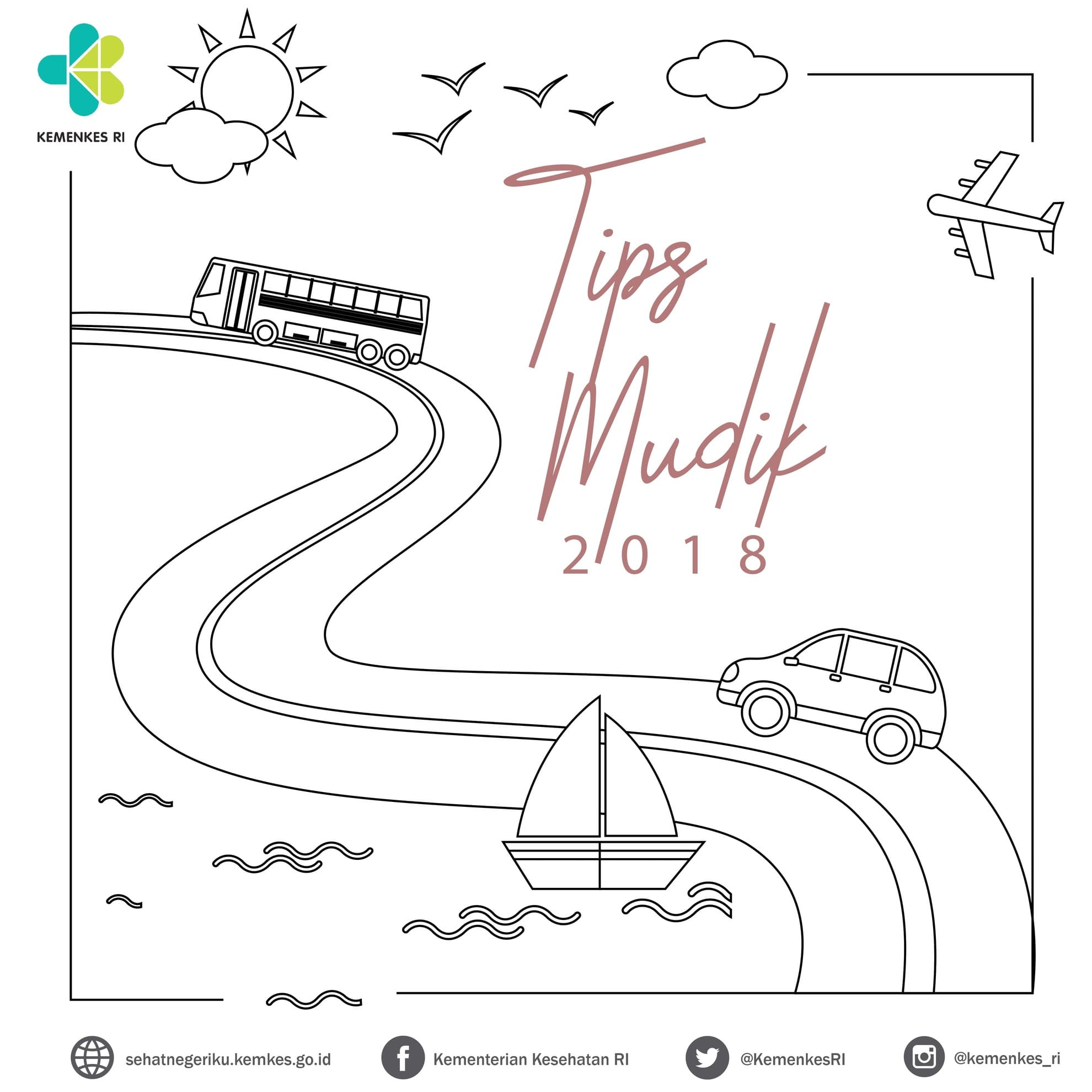Roni, bukan nama sebenarnya. Anak semata wayang dari orang tua yang sangat menyayangi dan banyak harta. Tinggal di Pujorahayu, Belitang OKU Timur Sumatera Selatan. Sayang selepas SMA, gagal melanjutkan kuliah pada salah satu fakultas di Universitas Lampung Tanjung Karang. Ia gagal bukan karena bodoh, malas atau drop out, tapi karena sakit jiwa yang tak kunjung sembuh, walau pengobatan telah puluhan tahun dilakukan.
Kini, Roni hanya tinggal bersama ibunya Atik (samaran) yang sudah mulai lemah, menderita berbagai penyakit komplikasi. Roni dan ibunya sama-sama sakit. Keduanya memerlukan orang lain untuk membantunya. Syukurlah, mereka dikaruniai harta yang berkecukupan, sehingga berbagai kebutuhan dapat dipenuhi, tanpa hambatan yang berarti. Roni, teman akrab sewaktu kecil. Selalu bersama dalam suka dan duka. Bersama satu sekolah, mulai dari SD, SMP dan SMA, bahkan bersama dalam bermain bola kaki, bola voli dan kasti. Ceria, bersorak dan bertepuk tangan menyambut cemesan bola voli yang menukik atau tendangan gol ke gawang lawan. Tak mengira, bila kemudian hari Ia menjadi merana, kemana mana sendiri, sebatang kara, tak ada teman dan handai tolan yang menemaninya. Ia asik sendiri dengan dunianya.
Kepiluan itu bermula tahun 1985, ketika Roni berniat meneruskan kuliah diUniversitas Sriwijaya (Unsri) Palembang. Mendengar saya akan mendaftar ke Universitas Lampung (Unila), Tanjung Karang. Ia pun urung ke Unsri, kemudian ikut ke Unila. Orang tuanya juga menyetujui, sebab diUnila juga banyak saudara yang telah kuliah lebih dahulu. Berangkat menuju Tanjung Karang dengan semangat 45. Menumpang bus angkutan lawas berbekal beberapa lembar kain ganti untuk 15 hari. Sampai di Tanjung Karang, kami numpang nginap dikamar kos saudara yang cukup besar berpenghuni 7 orang. Sambutan dari saudara sangat antusias, karena akan tambah saudara baru yang sedang menuntut ilmu di Tanjung Karang. Malam kedua, sekitar pukul 21.00 melihat gejala aneh pada Roni. Ia menyebar seluruh uang saku di tempat tidur. Hatiku bertanya-tanya, apakah mau pamer uang ? Tak berkomentar, hany amengamati dari jauh. Tapi, setengah jam kemudian, tampak Ia sedang menutupkan kedua belah tangan dan menempelkan di dada, seperti menyembah. Tak lama kemudian keluar kos dan mengembara ke jalan raya. Akhirnya, keesokan hari diantar pulang ke kampung. Kepiluan itu kian bertambah menyayat hati, ketika kampung, kemudian berkunjung kerumahnya dengan membawa 4 anak laki-laki yang sehat dan ceria. Terlihat di wajah Atik, tatapan
sedih dan rasa kehilangan yang sangat mendalam. Salah satu kepiluan anggota masyarakat yang anggotanya menderita gangguan kesehatan jiwa.
Kini, banyak anggota masyarakat yang bernasib sama, sedih dan pilu karena ada anggota keluarga yang mengalami hidup dengan gangguan kesehatan jiwa. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2007 jumlah pasien dengan gangguan jiwa beratadalah 4,6 per seribu penduduk. Sehingga diperkirakan jumlah pasien pada kelompok usia 15-64 tahun adalah 650.000-700.000 orang. Dari kepustakaan diketahui pula bahwa dengan pengobatan yang efektif, 50% pasien akan sembuh/pulih, 25% akan sembuh tetapi membutuhkan dukungan yang kuat dari orang lingkungannya, 15% tidak menunjukkan perbaikan yang berarti yang biasanya membutuhkan perawatan di rumah sakit, sedangkan 10% sama sekali tidak menunjukkan perbaikan.Tidak diperoleh data nasional jumlah orang yang dipasung. Jika diperkirakan setiap kecamatan mempunyai 2 hingga 5 orang. Jika jumlah kecamatan 5.263 (2005) maka diperhitungkan jumlah orang yang dipasung 10.000 – 26.000 orang.
Berbagai alasan mengenai mengapa mereka dipasung. Sebagian masyarakat memasung anggota keluarganya untuk melindungi dari kecelakaan. Seorang kader di suatu daerah memberikan kesaksian bahwa adiknya dipasung karena kecenderungan melemparkan dirinya ke dalam api. Ibu yang lain meminta warga memasung putranya karena tidak mampu menjaga. Putranya sering bepergian tanpa tujuan dan setelah beberapa hari diantar pulang oleh petugas. Hindari pemasungan Anggapan sebagian orang bahwa pasung dan penelantaran hanya terjadi di pedesaan, karena mereka menganut logika bahwa pemasungan terjadi karena akses yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi pada kenyataannya warga di kota besar juga melakukan pemasungan meskipun dengan cara yang berbeda.
Jika di pedesaan penderita dipasung pada halaman belakang rumah jauh maupun dekat, sehingga warga desa yang lain dapat melihat atau menonton jika mereka berteriak atau karena tingkah lakunya, tidak demikian halnya diperkotaan. Pasien dikurung didalam kamar untuk menutupi rasa malu bagi keluarga. Untuk menghindari pemasungan dan penelantaran, pemerintah sejak zaman Belanda telah berusaha mengurangi dengan menerapkan kebijakan yang humanis. Belanda mengikuti gerakan moral Eropa dan Amerika abad ke 20. Penderita gangguan jiwa yang disel dalam penjara (asilum) dibebaskan dan dirawat dengan perhatian. Sedangkan di Indonesia dengan cara membangun rumah sakit jiwa berkapasitas besar untuk menampung penderita yang menggelandang dan dipasung.
Rumah sakit dilengkapi dengan berhektar-hektar lahan untuk dikelola sebagai sarana rehabilitasi dan sumber kehidupan bagi rumah sakit. Sayang, setelah penderita pulih, tidak diikuti dengan perawatan lanjutan dan berobat jalan. Hal ini terjadi karena keterbatasan ekonomi dan pengetahuan. Sehingga baru beberapa minggu atau bulan dirumah pasien diantarkan kembali kerumah sakit. Namun, karena berbagai keterbatasan pengetahuan, jarak yang jauh, atau tidak mempunyai harapan, pasien dipasung atau ditelantarkan menggelandang. Bahkan terjadi juga keluarga dan masyarakat yang trauma dengan tingkah laku penderita, kemudian menolak pasien kembali. Mereka mengajukan permintaan tertulis kepada pemerintah setempat/pihak keamanan yang disertaiancaman bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada kehidupan pasien. Ini bentuk kepiluan lain atas keterbatasan pengetahuan dan ekonomi. Semoga dengan semangat “ Indonesia Bebas Pasung2014”, dapat secara bertahap mengurangi kepiluan itu.
Prawito