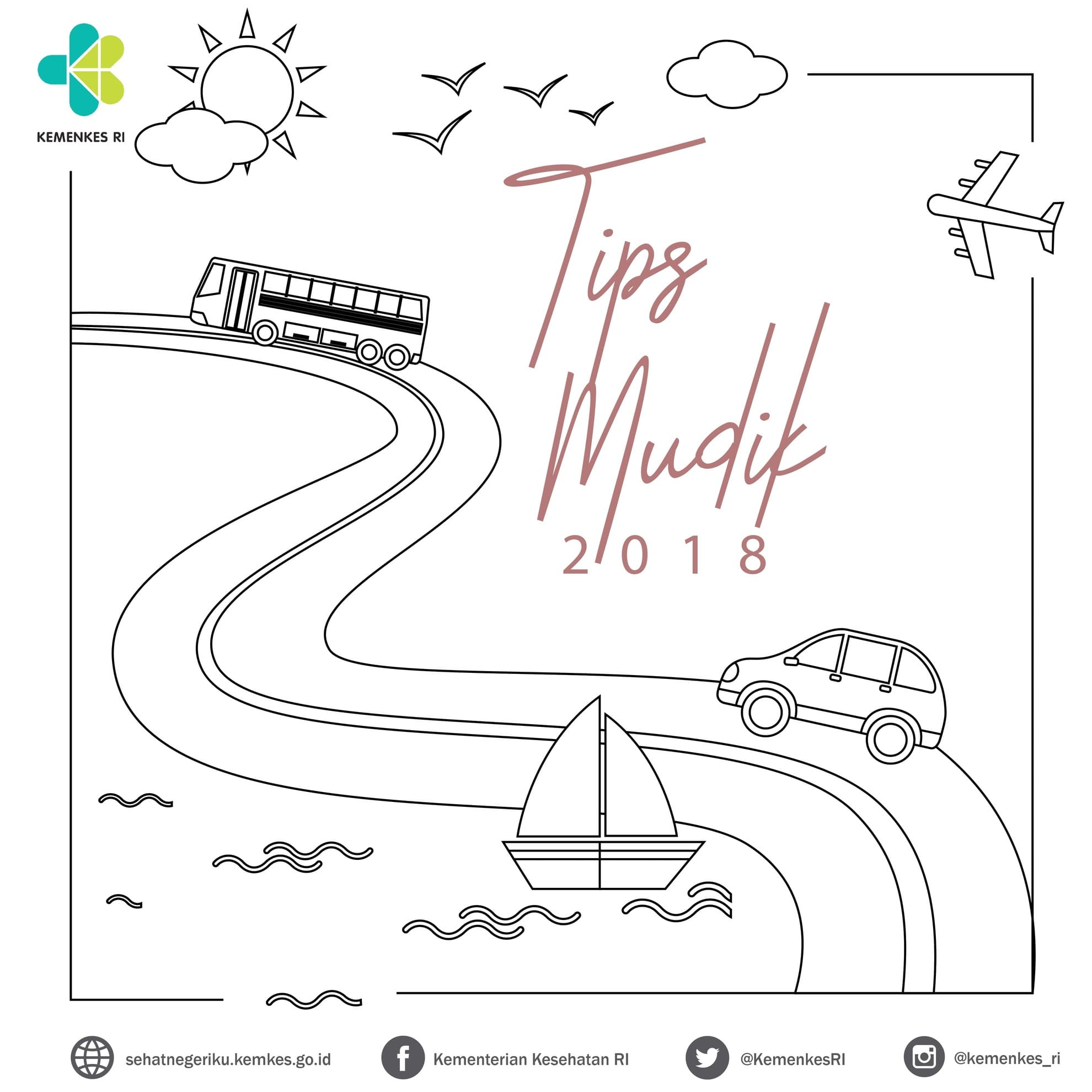Setiap orang punya inner child, sisi anak kecil dalam diri kita. Trauma masa lalu kadang perlu ditangani dengan terapi tertentu dan bantuan orang lain.
Inner child merupakan sosok anak kecil yang ada dalam diri seseorang. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh psikolog Swiss, Carl Jung. “Kalau kita merasa sudah dewasa tapi kok masih kekanak-kanakan, jangan-jangan sisi anak kecil dalam diri kita masih ada,” kata psikolog Samanta Elsener dalam Siaran Sehat di Radio Kesehatan pada 12 Februari 2024.
Seiring berkembangnya ilmu psikologi dari berbagai literasi dan penelitian, lahir istilah baru inner child trauma. Kondisi ini menunjukkan seseorang memiliki isu di masa kecil berupa trauma yang belum tuntas atau belum bisa berdamai dengan hal tersebut. Trauma tersebut kemudian akan mengganggu kehidupan sehari-harinya hingga dewasa.
“Inner child trauma itu bisa bermacam-macam. Enggak haus berkaitan dengan peran orang tua atau apa yang dialami di rumah tapi bisa juga berkaitan dengan apa yang kita alami di sekolah,” ujar Samanta. Dia mencontohkan ketika seseorang pernah mengalami perundungan (bullying) di sekolah, maka dewasa nanti mungkin ia belum bisa memaafkan kondisi tersebut sehingga kemampuannya dalam interaksi sosial menjadi sulit.
Menurut Carl Jung, semua orang memiliki inner child. Ini sama dengan sifat heroik yang tertanam pada diri seseorang, seperti rasa ingin menolong, berbuat baik, dan menunjukkan sikap altruisme. Namun, tidak semua orang memiliki inner child trauma.
Menurut Samanta, trauma itu sangat subjektif. Ada anak yang baru menyadari bahwa dirinya punya trauma saat sudah dewasa. Misalnya, seseorang mengalami pelecehan seksual saat berusia lima tahun tapi tidak memahami perilaku tersebut. Ketika beranjak dewasa dan mulai mempelajari konten edukasi seputar psikologi dan kesehatan metal, secara tidak sadar dia mengingat kembali peristiwa yang dialami saat berusia lima tahun tersebut dan akhirnya baru menyadari bahwa dirinya memiliki trauma. “Bisa jadi inner child trauma sudah menjadi suatu kebiasaan dari perilakunya tapi dia tidak menyadari kenapa berperilaku seperti itu.”
Trauma juga bisa dikenali dari body sensation, seperti rasa tidak nyaman, tangan tiba-tiba berkeringat, dan sebagainya. Contohnya adalah sikap antipati terhadap lawan jenis. Setiap kali berdekatan dengan lawan jenis, dia selalu menolak, badan merasa tidak nyaman, dan kemudian menarik diri sehingga tidak ingin menjalin hubungan dan tidak ingin menikah.
Apabila ditelusuri lebih lanjut dengan konseling dan psikoterapi, ternyata orang tersebut punya trauma masa kecil, misalnya karena salah satu orang tuanya pernah meninggal secara mendadak dan rasa duka dalam dirinya belum hilang. “Baginya, lawan jenis itu membuat dia teringat dengan masa dukanya. ‘Aduh, kalau nanti tiba-tiba ditinggal bagaimana, ya?’ Rasanya kan sedih sekali,” tutur Samanta.
Konsep inner child juga berhubungan dengan harapan-harapan di masa kecil yang belum terpuaskan. Misalnya, orang tua kita dahulu tidak bisa membelikan video game karena tidak mampu. Pada saat beranjak dewasa dan merasa mampu, kita akan membeli video game dan memainkannya hingga lupa waktu. Kondisi ini disebut sebagai reparenting atau menyuapi sisi anak kecil dalam diri yang kebutuhan dan keinginannya belum terpenuhi.
Mengenali inner child dalam kehidupan menjadi hal yang penting, termasuk bagi pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan. Samanta menganjurkan mereka untuk melakukan sesi konsultasi sebagai persiapan sebelum menikah. Hal ini perlu agar mereka mengetahui karakter masing-masing dan meminimalkan terjadinya konflik dalam rumah tangganya kelak sehingga mereka tidak mewariskan inner child yang belum selesai pada keturunannya.
“Kalau gen Z, rata-rata sudah paham. Jadi, sebelum menikah mereka mau melakukan konsultasi. Kira-kira potensi konfliknya bagaimana dan apa saja. Mereka mau belajar cara berkomunikasi yang baik terhadap pasangannya,” kata Samanta.
Bahkan, menurut Samanta, generasi Z rela menabung demi melakukan sesi konsultasi bersama dengan psikolog karena merasa sangat butuh. Jadi, komitmen mereka untuk memutus mata rantai inner child maupun trauma sangat besar demi perubahan hidup.
Untuk inner child yang tidak terluka, reparenting bisa menjadi salah satu teknik untuk berdamai dengan sosok anak kecil dalam diri kita. Kita perlu mengidentifikasinya terlebih dahulu dengan berkonsultasi pada psikolog. Bila emosi anak-anak yang belum selesai ini akibat orang tuanya pernah meninggalkan atau tidak hadir saat anaknya membutuhkan, maka fokuslah pada emosinya terlebih dahulu. Kemudikan lakukan reparenting dengan melakukan self talk, mengajarkan diri sendiri bagaimana bisa mempercayai orang kembali.
Samanta berpesan agar orang tidak takut untuk melakukan check up mengenai kesehatan mentalnya. “Kalau kita suka berasumsi dengan membaca literasi yang beredar, ya itu benar bisa megedukasi kita tapi kita enggak bisa self diagnose karena akan semakin berbahaya dan muncul mental playing victim. Hal ini menjadikan diri kita sebagai korban dan akhirnya kita jadi enggak bisa maju untuk mencapai apa pun yang menjadi cita-cita kita saat ini.”
Penulis: Redaksi Mediakom